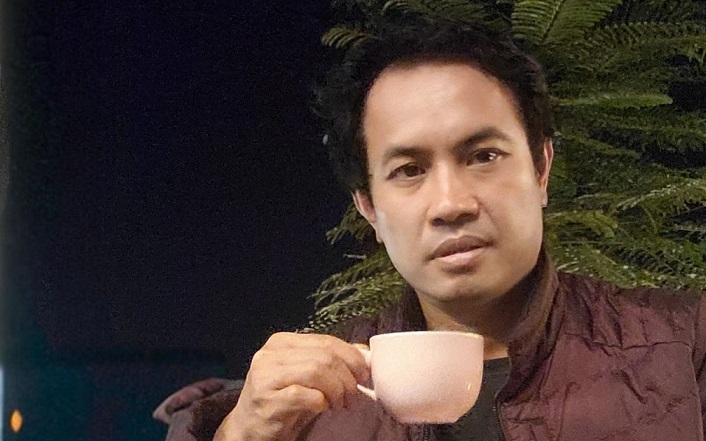Batam tampaknya telah naik kelas bukan lagi sekadar kawasan perdagangan bebas, melainkan kini “surga baru bagi limbah beracun dunia.” Tujuh puluh tiga kontainer limbah B3 elektronik yang disegel di pelabuhan menjadi saksi bisu betapa rapuhnya garda lingkungan negeri ini. Kota industri yang seharusnya menjadi simbol kemajuan kini berubah menjadi tempat pembuangan sampah global, sebuah ironi di tengah pidato pemerintah tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Kedaulatan Lingkungan yang Bocor di Pelabuhan Sendiri
Secara normatif, hukum Indonesia tidak kekurangan pasal untuk melindungi lingkungan dari ancaman limbah beracun. Pasal 69 ayat (1) huruf c, d, dan f Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) secara tegas melarang siapa pun memasukkan limbah berbahaya dan beracun ke wilayah NKRI. Namun, ketika puluhan kontainer e-waste bisa lolos dan berlabuh di Batam, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kedaulatan lingkungan hidup telah bocor di pelabuhan sendiri.
Kementerian Lingkungan Hidup mungkin berusaha mengatur re-ekspor, namun pertanyaan mendasarnya tetap: bagaimana limbah itu bisa masuk? Apakah aparat pengawas lengah, atau justru sengaja memejamkan mata di bawah gemerincing ekonomi impor? Ironisnya, dalam setiap kasus, hukum sering berhenti pada pelaku teknis di lapangan sementara aktor administratif yang sesungguhnya bertanggung jawab tetap aman di balik meja.
Pola ini menunjukkan bahwa kebocoran pengawasan bukan semata karena lemahnya sistem, melainkan karena adanya “ruang kompromi” antara pejabat dan pelaku ekonomi. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan, bisik-bisik tentang kongkalikong pejabat BP Batam dengan eksportir limbah B3 semakin santer terdengar. Modusnya klasik namun efektif: dokumen asal-usul limbah dimanipulasi, klasifikasi bahan berbahaya diubah menjadi bahan olahan industri, dan seluruhnya tampak sah di atas meja pejabat. Akibatnya, kontainer berisi e-waste dari luar negeri dapat masuk seolah barang biasa. Yang menarik, Kepala BP Batam yang juga ex officio Wali Kota Batam disebut murka. Ia merasa terjebak dalam jaringan birokrasi yang saling menutupi.
Membaca Sikap Kepala BP Batam: Hukum di Atas Segalanya
Ketika isu impor limbah B3 dari Amerika Serikat menyeruak di Pelabuhan Batu Ampar, publik sontak menuding lemahnya pengawasan sebagai biang keladi. Namun di tengah gempuran opini dan desakan publik, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengambil langkah yang berbeda: menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bagi sebagian orang, sikap ini mungkin tampak sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab. Namun, jika dicermati secara hukum dan tata kelola pemerintahan, langkah itu justru mencerminkan ketaatan pada prinsip due process of law. Bahwa penegakan hukum lingkungan harus berjalan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan lintas lembaga.
Dalam pernyataannya kepada Teras Batam (7 Oktober 2025), Amsakar menegaskan: “Kalau sudah masuk ke ranah hukum, maka proses penegakan hukumnya harus dijalankan, apalagi jika sudah masuk tahap eksekusi.”
Pernyataan ini menggambarkan kesadaran penting bahwa kasus limbah B3 bukan sekadar urusan administratif pelabuhan, tetapi menyentuh aspek hukum pidana lingkungan dan tanggung jawab internasional. Oleh karena itu, menyerahkan kasus ini ke KLHK sebagai lembaga yang memiliki otoritas teknis dan yuridis di bidang pengawasan bahan berbahaya dan beracun merupakan langkah konstitusional dan prudent, bukan bentuk cuci tangan.
Perlu dipahami, struktur BP Batam sebagai badan pengusahaan memiliki mandat ekonomi dan investasi, bukan sebagai lembaga penegak hukum lingkungan. Dalam konteks inilah, langkah koordinatif yang diambil oleh Amsakar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi penting. Ia memastikan agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial di Batam. Batam sebagai sebuah kawasan industri yang menyerap ribuan tenaga kerja. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip integratif antara pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum lingkungan, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Selain itu, dukungan BP Batam terhadap proses hukum yang dilakukan KLHK dan Bea Cukai menunjukkan transparansi yang jarang terlihat dalam penanganan kasus lingkungan serupa. Dari total 74 kontainer yang ditemukan, sebanyak 61 kontainer telah selesai diperiksa fisik, sementara sisanya masih menunggu tahap pemeriksaan bersama KLHK. Proses ini dilakukan secara terbuka, dan setiap hasil pemeriksaan dilaporkan ke publik. Transparansi ini justru menjadi indikator bahwa BP Batam tidak berupaya menutup-nutupi persoalan, melainkan mempercepat solusi dengan menyerahkan perkara kepada otoritas hukum yang tepat.
Kemarahan Amsakar, yang sebelumnya diberitakan muncul akibat adanya dugaan kongkalikong di level pejabat teknis, dapat dibaca sebagai bentuk reaksi moral dari seorang kepala lembaga yang merasa dikhianati oleh sistem birokrasi di bawahnya. Ia tidak marah karena ingin lepas tangan, melainkan karena sistem yang seharusnya ia pimpin dengan kendali penuh ternyata disusupi oleh kepentingan yang menyimpang. Dalam konteks ini, Amsakar sedang berhadapan dengan paradoks birokrasi: antara tanggung jawab politik sebagai wali kota dan kendali administratif sebagai kepala BP Batam yang terikat struktur pusat.
Maka, menyerahkan kasus ini ke KLHK bukanlah bentuk lari dari tanggung jawab, melainkan bukti kedewasaan kelembagaan. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks seperti Batam yang mana terkadang kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan bertabrakan. Maka, keputusan untuk tunduk pada jalur hukum adalah pilihan yang paling rasional dan beradab.
Jika langkah seperti ini dijalankan secara konsisten, maka kasus limbah B3 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga, memperjelas batas kewenangan, dan mendorong transparansi tata kelola pelabuhan. Dalam jangka panjang, justru sikap seperti Amsakar-lah yang menjadi cermin pejabat publik yang memahami batas kekuasaan dan menghormati supremasi hukum.
Mandulnya Penegakan Hukum dan Prinsip Strict Liability
Dalam hukum lingkungan, tidak ada alasan untuk berkelit. Pasal 88 UUPPLH menetapkan prinsip strict liability bahwa setiap pihak yang menggunakan, menghasilkan, atau mengelola limbah B3 bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun dalam praktik, prinsip ini hanya hidup di seminar, bukan di ruang sidang.
Jika negara benar-benar konsisten, maka korporasi pengirim dan penerima limbah harus dituntut dengan pasal 116 sd 118 tentang pidana korporasi. Pejabat publik yang lalai mengawasi seharusnya dijerat dengan Pasal 111 tentang penyalahgunaan wewenang. Sayangnya, yang kita saksikan justru panggung politik: menteri dipersalahkan, pejabat saling lempar pernyataan, dan publik disuguhi drama re-ekspor yang lebih mirip sinetron daripada penegakan hukum.
Re-ekspor limbah ke negara asal bukan kemenangan diplomasi, melainkan pengakuan atas kegagalan deteksi dini. Dalam prinsip environmental governance, tindakan itu hanyalah langkah darurat setelah kerusakan terjadi. Lebih parah lagi, setiap kontainer yang lolos merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Basel 1989 yang telah diratifikasi lewat Keppres No. 61/1993 dilihat sebagai suatu pelanggaran hukum internasional yang seharusnya membuat Indonesia menggugat, bukan sekadar memulangkan.
Batam sebagai Cermin Krisis Tata Kelola dan Moral Lingkungan Nasional
Kasus Batam bukanlah anomali, melainkan gejala dari penyakit nasional: lemahnya tata kelola lingkungan yang ditelan birokrasi ekonomi. Selama izin impor masih dianggap ladang retribusi, selama aparat lebih takut pada atasan daripada pada undang-undang, dan selama politik sibuk mencari kambing hitam ketimbang memperbaiki sistem, maka Indonesia akan terus menjadi landfill global tempat buangan limbah.
Kita boleh berbicara tentang green industry dan net zero emission, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelabuhan kita belum mampu menolak limbah beracun. Jalan keluarnya bukan pada pidato, melainkan sistem. Ada lima langkah yang harus segera dilakukan:
- Audit total izin impor dan audit etik pejabat terkait.
- Digitalisasi seluruh izin dan manifest logistik berbasis blockchain agar tidak bisa dimanipulasi.
- Penegakan nyata Pasal 88 dan 116 dengan menjerat korporasi, bukan buruh pelabuhan.
- Pembentukan Satgas Lingkungan Independen yang melibatkan jaksa, akademisi, dan auditor lingkungan.
- Revisi kewenangan BP Batam agar fungsi pengawasan lingkungan tidak dikorbankan demi promosi investasi.
Batam adalah gerbang ekonomi bagian barat Indonesia, dan karenanya menjadi cermin moral bagi seluruh negeri. Negara ini terlalu sering mengaku cinta alam, tetapi terus membiarkan laut dan tanahnya diracuni. Selama pejabat lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan integritas, limbah akan terus menemukan surganya di pelabuhan kita. Jika hukum lingkungan terus dianggap dokumen mati, maka tak lama lagi bukan hanya Batam tetapi seluruh Indonesia akan menjadi “surga limbah” paling indah di Asia Tenggara. ***